Kim Jong Un memiliki senjata nuklir untuk mencegah serangan dari Amerika. Karenanya, terdapat sebuah solusi teraneh untuk membatasi persenjataan Korea Utara adalah dengan membantu mereka agar mereka tidak merasa perlu memiliki nuklir untuk mencegah sebuah serangan. Itulah yang menjadi logika proposal oleh Lyle Godlstein, seorang Profesor Universitas Perang Angkatan Laut yang sangat kontra-intuitif namun anehnya menarik, yang mengatakan: Amerika Serikat sebaiknya meminta China dan Rusia untuk menyebar pasukannya ke wilayah Korea Utara.
Oleh: Peter Binart (The Atlantic)
“Pemerintahan Amerika Serikat (AS) memiliki kebiasaan lama menggambarkan musuhnya setinggi 10 kaki—dan gila,” seperti yang pernah ditekankan oleh Fareed Zakaria. Oleh karenanya, Penasihat Keamanan Nasional H.R. McMaster pada bulan Desember menyebut program senjata nuklir Korea Utara—yang menurut intelijen Amerika masih belum memiliki kapabilitas untuk menyerang AS —”perkembangan yang paling menunjukkan perusakan stabilitas, menurut saya, dalam masa pasca-perang dunia II.” Lebih rusuh, bahkan, daripada persenjataan Stalin dan Mao yang jauh lebih besar; atau dari pecahnya Kerajaan Inggris, Prancis, dan Soviet; atau kebangkitan China; atau perubahan iklim yang dalam waktu dekat akan membuat banyak kota menjadi tidak layak huni. Jika program nuklir pemerintah Korea Utara diperbolehkan untuk dilanjutkan, sambung McMaster, maka Korea Utara—yang GDP-nya hanya seperlimapuluh dari negara Korea Selatan dan menghabiskan seperlimanya untuk pengembangan militer—mungkin saja “mempersatukan kembali Semenanjung Korea di bawah ‘bendera merah’”.
Menggambarkan program nuklir Korea Utara sebagai ekspresi atas kekuatan geopolitiknya itu memang salah. Program tersebut sebenarnya merupakan buah dari kelemahan Korea Utara yang luar biasa. Itulah mengapa strategi pemerintahan Trump yang mengancam Korea Utara dengan perang—dan membuat mereka semakin merasa terancam—merupakan cara yang salah untuk mengekang program nuklir mereka. Kim Jong Un memiliki senjata nuklir, lebih daripada yang lain, untuk mencegah serangan yang datang dari Amerika. Karenanya, solusi teraneh untuk membatasi persenjataan mereka adalah dengan membantu mereka agar mereka tidak merasa perlu memiliki nuklir untuk mencegah sebuah serangan. Itulah yang menjadi logika proposal oleh Lyle Godlstein, seorang Profesor Universitas Perang Angkatan Laut yang sangat kontra-intuitif namun solusi teraneh tersebut terlihat menarik , yang mengatakan: Amerika Serikat sebaiknya meminta China dan Rusia untuk menyebar pasukannya ke wilayah Korea Utara.
Untuk memahami alasan Goldstein yang memberikan solusi teraneh, kita perlu mencerna bagaimana meningkatkan kelemahan Korea Utara menjadi faktor pendorong program nuklir mereka. Ilmuwan Politik Stanford bernama Scott Sagan telah mengamati bahwa “kebanyakan penstudi Hubungan Internasional memiliki jawaban yang singkat dan jelas” mengenai kenapa negara tersebut mengembangkan senjata nuklir. Mereka melakukannya “ketika mereka menghadapi ancaman militer yang signifikan atas keamanan mereka yang tidak dapat diatasi dengan cara alternatif.” Selama setengah abad terakhir, ancaman militer ke Korea Utara semakin meningkat, sementara langkah alternatif yang dapat mereka gunakan untuk melindungi diri mereka sendiri semakin sedikit. Itulah yang menjadi latar belakang perburuan obsesif Pemerintah Korea untuk memiliki senjata nuklir.
Pertama, pertimbangannya yang memberikan solusi teraneh ialah pergeseran keseimbangan kekuatan antara Pyongyang dan Seoul. Korea Utara telah lama memiliki populasi yang lebih sedikit dari Korea Selatan. Namun hinggal awal tahun 1970-an, kedua negara tersebut memiliki GDP per kapita yang hampir sama jumlahnya. Sekarang, GDP Korea Selatan sekitar 23 kali lipat lebih tinggi. 92 persen jalan-jalan di Korea Selatan telah diaspal. Di Korea Utara, baru tiga persen jalan yang diaspal. Rata-rata penduduk Korea Selatan hidup satu dekade lebih lama daripada penduduk Korea Utara, mereka juga memiliki tinggi badan 1 sampai 3 inci lebih tinggi.
Korea Utara telah mencoba menjaga kiprah militer mereka dengan mencurahkan seperempat GDP mereka untuk pertahanan. Mereka juga memiliki lebih banyak penduduk yang mengabdi menjadi militer ketimbang Korea Selatan. Namun jurang teknologi antara kedua negara telah berkembang semakin ekstrem.
Pesawat tempur yang paling umum dimiliki Korea Utara dirakit pada tahun 1953. Sementara Korea Selatan, menurut laporan dari Pusat Strategi dan Studi Internasional tahun 2011, telah “telah mencapai keunggulan besar dalam pesawat tempur modern dan misil darat-udara.” Pola yang sama juga tampak di daratan. Korea Utara, seperti yang ditekankan Goldstein, memiliki “tank dari tahun 1950-an dan mereka tidak memiliki bahan bakar untuk tank tersebut. Mereka juga tidak mampu menghidupi para tentara yang menjalankan tank tersebut.”
Namun ini hanyalah sebagian dari cerita dari solusi teraneh tersebut. Korea Utara tidak hanya menjadi jauh lebih lemah ketimbang musuhnya Korea Selatan, ia juga menjadi jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan negara-negara adidaya. Selama perang dingin, Korea Utara dan Korea Selatan sama-sama memiliki pelindung penting, yang berperang bersama mereka dalam perang Korea. Kemudian pada tahun 1991, sekutu paling kuat Korea Utara, Uni Soviet, terpecah. Negara penerusnya, Rusia, membatalkan kesepakatan bantuan timbal balik dengan pemerintah Korea Utara, dan membuka hubungan diplomasi dengan Pemerintah Korea Selatan. Hingga tahun 1992, Angkatan Laut Rusia dan Korea Selatan saling mengunjungi pelabuhan satu sama lain.
Di waktu yang sama, sekutu besar Korea Utara yang lainnya, China, juga mulai menjalin hubungan dengan Korea Selatan, bahkan perdagangan di antara kedua negara tersebut dengan cepat melampaui perdagangan antara Korea Utara dengan China. (Korea Selatan sekarang merupakan rekan perdangangan terbesar keempat China. Korea Utara bahkan tidak masuk dalam peringkat 15 teratas.) Hubungan China dengan Korea Utara, secara kontras, tumbuh semakin dingin. Dalam bukunya, No Exit: North Korea, Nuclear Weapons, an International Security, Jonathan Pollack menekankan bahwa Pendiri Korea Utara, Kim Il Sung, mengunjungi China setiap tahunnya. Penerusnya, Kim Jong Il, yang naik tahta pada tahun 1994, tidak mengunjungi China hingga tahun 2000.
Semua kejadian tersebut mungkin saja masih dapat dihadapi oleh Pemerintah Korea Utara jika mereka dapat mempererat hubungan dengan sekutu Korea Selatan, Amerika Serikat. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi. Hubungan Korea Utara dengan Jepang juga sama nasibnya. Justru, Amerika Serikat—yang semakin yakin bahwa diktatorisme harus enyah dari muka bumi—menunggu nasib Korea Utara agar mengalami apa yang dialami Jerman Timur. Yang membuat pemerintah Korea Utara semakin tidak percaya diri adalah, bahwa AS masih melanjutkan latihan militernya dengan Korea Selatan bahkan setelah Perang Dingin selesai. Seorang anggota Kongres yang bertemu dengan Kim Il Sung pada tahun 1993 melaporkan, bahwa ketika mendiskusikan pemainan perang yang dilakukan oleh AS-Korea Selatan, suara Pemimpin Korea Utara “bergetar dan tangannya gemetaran karena amarah.”
“Mungkin masih sulit bagi kebanyakan orang untuk memahami bagaimana mendalamnya perasaan Korea Utara mengenai krisis yang mereka alami” sebagai dampak dari pergeseran tektonik, tulis Fu Ying, Kepala Komite Akademik di Institut Negeri Strategi Global di Ilmu Sosial Akademi China. Korea memulai program nuklir mereka di bawah pengawasan Uni Soviet pada tahun 1950-an. Namun, kemungkinan besar Pemerintah USSR waktu itu tidak benar-benar menginginkan Korea Utara untuk membuat bomb, dan bila USSR tidak terpecah, mungkin Korea Utara sendiri juga tidak benar-benar ingin membuat bomb. “Peristiwa yang terjadi di awal tahun 1990-an sangat mengejutkan bagi Korea Utara dan membuat mereka memutuskan untuk mengambil solusi teraneh,” tulis Fu, “termasuk dengan memilih opsi nuklir.” Pada tahun 1990, satelit Amerika menangkap bukti bahwa Korea Utara telah mengembangkan fasilitas nuklir secara rahasia di Yongbyon.
Semenjak itu, posisi geopolitik Korea Utara semakin bertambah buruk. Sebagai dampak dari Perjanjian Kerangka Kerja 1994—yang menutup Yongbyon—Pemerintahan Clinton menekankan pada tahun 2000 bahwa mereka tidak memiliki “maksud buruk” kepada Pemerintah Korea Utara. Namun, baik Korea Utara maupun Amerika Serikat melanggar perjanjian tersebut, dan ketika Pemerintahan Bush mengambil alih jabatan, mereka tidak mau mengulang janji Amerika kepada Korea Utara bahwa Amerika tidak memiliki maksud buruk. Berlawanan dengan hal tersebut, George W. Bush menyebut Korea Utara sebagai anggota dari “Poros Penjahat,” dan kemudian menyerang Irak. Wakil Menteri Luar Negeri John Bolton menginstruksikan kepada Pemerintahan Korea Utara untuk “mengambil pelajaran penting.”
Semenjak itu, Korea Utara kembali melihat Amerika menggulingkan diktator lain yang tidak memiliki senjata nuklir: Muammar Qaddafi. Mereka melihat AS mempraktikkan “serangan pemenggalan kepala” terhadap rezim mereka. Mereka melihat Donald Trump mendeklarasikan—sebagai respon terhadap pertanyaan mengenai rencana pembunuhan Kim Jong Un—bahwa “saya pernah mendengar hal yang lebih buruk.” Mereka juga telah melihat pemerintahan Trump mengancam akan melakukan pergerakan untuk perang.
Mereka juga menyaksikan China—sekutu terakhir mereka—semakin condong ke arah Korea Selatan. Semenjak menjadi pemimpin China di tahun 2012, Xi Jinping telah menemui perwakilan Korea Selatan sebanyak tujuh kali. Dia sama sekali belum pernah bertemu dengan Kim Jong Un. Pemerintah China telah memutuskan untuk mendukung sanksi PBB yang diberikan kepada Korea Utara. Pemerintah China bahkan mendeklarasikan bahwa mereka tidak lagi merasa memiliki ikatan untuk mempertahankan pemerintah Korea Utara di bawah Mutual Aid and Cooperation Friendship Treaty yang ditandatangani kedua negara pada tahun 1961.
Dalam perihal keamanan, dengan kata lain, Korea Utara melihat senjata nuklir sebagai satu-satunya pilihan yang mereka miliki yang merupakan solusi teraneh bagi negara lain.
Yang menjadi permasalahan dengan program nuklir Korea Utara bukanlah bahwa Kim Jon Un memiliki rencana untuk menggunakannya. Dia telah menunjukkan bahwa ia tak memiliki maksud untuk bunuh diri. Yang menjadi permasalahan ialah bahwa mereka memainkan permainan rezim yang tertutup dan paranoid, yang memiliki sedikit hubungan dan komunikasi yang baik dengan Gedung Putih, yang juga memiliki pandangan tertutup dan paranoid. Yang lebih membahayakan adalah bahwa Korea Utara mungkin saja sangat putus asa dengan kondisi ekonomi mereka, sehingga mereka memustukan untuk menjual teknologi nuklir mereka kepada aktor yang memiliki watak lebih buruk.
Namun jika kita ingin agar Korea Utara meninggalkan, atau membatasi persenjataan nuklir mereka, kita harus meyakinkan pemimpin mereka bahwa mereka masih dapat bertahan tanpa senjata nuklir. Hal ini mungkin sulit dilakukan terlebih setelah intervensi yang terjadi di Libya, semenjak Kim melihat bagaimana Libya memilih meninggalkan program nuklir mereka agar menjalin hubungan lebih dekat dengan Amerika, dan pemerintahan mereka justru kemudian digulingkan oleh pihak Amerika. Pada titik ini, janji ketiaadaan perang yang ditawarkan Clinton pada tahun 2000—bahkan diikuti dengan pemberhentian latihan militer AS dengan Korea Selatan—kemungkinan besar tidak cukup untuk meyakinkan Korea Utara.
Inilah mengapa pembuat kebijakan Amerika perlu berpikir lebih keras untuk memberikan solusi teraneh. Rajan Menon dari Perguruan Tinggi Kota New York, menyarankan agar Amerika berjanji untuk menarik tentaranya dari Korea Selatan jika Korea Utara bersedia menghentikan perkembangan nuklir mereka. Namun—selain memperlemah posisi Amerika di Asia—mundurnya tentara Amerika dari Korea Selatan akan membuat Korea Selatan, dan mungkin juga Jepang, untuk mengembangkan senjata nuklir mereka sendiri. Hal itu akan membuat Korea Utara sama lemahnya seperti sekarang, dan semakin melekat dengan program nuklir mereka.
Gagasan Lyle Goldstein—yang disampaikannya secara singkat dalam bukunya yang terbit di tahun 2015, Meeting China Halfway, dan banyak dibahas setelahnya—berbeda. Daripada AS menarik tentaranya dari Korea Selatan, lebih baik sejumlah kecil tentara China atau mungkin Rusia, dengan izin pemerintah, dikirim ke Korea Utara.
Kecil kemungkinannya tentara tersebut akan membuat Kim Jong Un lebih berani. Malahan, tentara tersebut kemungkinan besar malah menahannya, apalagi melihat bahwa China dan Rusia sama-sama menghargai hubungan mereka dengan Korea Selatan. Namun dengan adanya solusi teraneh tersebut, tentara China dan Rusia di Korut, akan membuat Amerika ataupun Korea Selatan sangat sulit menyerang Korea Utara. Bahkan Pemerintahan Trump—yang secara menakutkan benar-benar bersedia mengobarkan perang dengan Korea Utara—tidak berani mengambil risiko untuk membunuh tentara China dan Rusia, yang kemungkinan besar memprovokasi perang dengan Rusia dan China. Dengan begitu Kim Jong Un akan merasa bahwa situasinya cukup aman baginya untuk membatasi, atau bahkan menghentikan, program pengembangan nuklirnya. Dia juga akan mendapatkan martabat. Menerima tentara China dan Rusia dapat menjadi pendorong kredibilitas seorang pemimpin yang saat ini bahkan tidak mampu menemuni Xi Jinping.
Kemudian kepada pemerintahan Amerika Serikat, Goldstein juga menyarankan solusi teraneh, yakni suatu kebijakan luar negeri yang berlawanan dari norma. Warga Amerika secara umum menganggap bahwa semakin besar keuntungan militer Amerika di suatu tempat, maka semakin amanlah mereka. Menyarankan bahwa Amerika dapat meningkatkan keamanannnya dengan memperbolehkan tentara China dan Rusia ke Semenanjung Korea—pada waktu dimana Trump mengumumkan bahwa sekarang adalah waktunya kompetesi negara adidaya era baru—merupakan suatu keputusan yang sangat berlawanan. Begitu juga dengan gagasan bahwa Amerika mungkin mendukung perlindungan terhadap rezim yang oleh Trump pernah disebut jahat.
Namun kekuatan radikal asimetris tidak selalu berada di pihak Amerika semenjak masa berakhirnya Perang Dingin. Mereka tidak berada di pihak Amerika ketika AS menyerang Afghanistan dan Irak—dua negara lain yang menjadi ‘yatim’ setelah keruntuhan pendukung lamanya, Uni Soviet. Mereka juga tidak berpihak kepada Amerika ketika mereka mencoba memburu senjata nuklir Korea Utara.
Selain itu, penyebaran tentara Rusia dan China mungkin tidak akan memperpanjang rezim Korea Utara. Justru kemungkinannya mereka akan meredam ketegangan, yang akan memperbesar kemungkinan terjadinya ikatan antara Korea Utara dan Korea Selatan, dan membiarkan pesona ekonomi dan budaya Korea Selatan menggerogoti totalirianisme Korea Utara dari dalam. Perlu diingat bahwa kesepakatan Helsinki tahun 1975, yang pada saat itu seolah menegaskan pembagian divisi di Eropa pada masa Perang Dingin, justru merusaknya dengan mendorong pemberontakan di wilayah Timur. Tidak ada yang dapat menjamin tentu saja. Namun jika sanksi dan strategi militer Amerika yang telah dilakukan semenjak 25 tahun belakangan ditujukan untuk membebaskan rakyat Korea Utara, hal tersebut telah menjadi kegagalan yang malang.
Perdebatan kebijakan luar negeri Washington menunjukkan sesuatu, ketika gagasan Goldstein dianggap terlalu radikal untuk mendapatkan perhatian serius, sementara gagasan McMaster dan Trump masih di awang-awang—serangan untuk mengulingkan Korea Utara yang dapat memicu perang yang akan membunuh setidaknya jutaan penduduk di Seoul—hal ini masih dianggap sebagai subyek perdebatan yang sah. Mungkin bukan musuh kita yang gila. Mungkin kita yang gila.
Sumber : Solusi Teraneh (dan Mungkin Terbaik) untuk Selesaikan Krisis Korea Utara
Results 1 to 1 of 1
-
12-02-18, 20:26 #1
 Solusi Teraneh (dan Mungkin Terbaik) untuk Selesaikan Krisis Korea Utara
Solusi Teraneh (dan Mungkin Terbaik) untuk Selesaikan Krisis Korea Utara







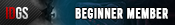




Share This Thread