Pola kekerasan, pertarungan elite politik, dan kontra intelijen memainkan peranan penting bagaimana ruang publik ini dibentuk. Kondisi ini bukan hanya bentuk perang urat syaraf, melainkan alarm bagi rezim yang berkuasa sekarang.
Oleh: Wahyudi Akmaliah
Di Istana Bogor, Sabtu, 10 Februari 2018, Presiden Joko Widodo memberikan pesan penting kepada Peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa. Selain menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Afghanistan yang mengalami konflik tidak berkesudahan, ia mengingatkan kembali mengenai Indonesia sebagai negara majemuk, memiliki rasa toleransi, dan kebersamaan yang kuat.
Di sini, para pemuka agama menjadi medium penyampai yang kuat untuk mengingatkan masyarakat terkait nikmatnya perdamaian dan persatuan. “Jangan sampai lupa tentang anugerah dari Tuhan mengenai ini. Jangan sampai kita lupa nikmatnya kerukunan, karena kita selama ini selalu rukun,” ujar Presiden.
Lebih jauh, ia kemudian mengatakan, “saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Din Syamsuddin, kepada seluruh pemuka agama, peserta musyawarah atas komitmennya untuk memperkuat kerukunan bangsa, serta atas komitmennya memperkokoh NKRI, memperkokoh Pancasila, serta memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika.”
Karena komitmen ini dan peran para pemuka agama tersebut, Indonesia dikenal dunia internasional sebagai negara penuh keragaman yang menjunjung tinggi toleransi. Indonesia juga menjadi “contoh masyarakat Muslim yang mengedepankan Islam moderat, contoh keberhasilan menjaga Bhinneka Tunggal Ika”.
Namun, ucapan Presiden dan pertemuan tokoh agama itu menjadi tamparan keras saat dihadapkan pada peristiwa pembacokan yang terjadi di pagi hari, tepatnya Minggu (11 Februari 2018). Saat jemaat sedang menjalankan ibadah misa di Gereja Santa Lidwina Bedog, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping Sleman, Yogyakarta, seorang pemuda masuk membawa pedang. Dengan pedangnya, ia menyerang umat dan pastor dengan membabi buta.
Akibat penyerangan tersebut, ada tiga umat dan Pastor Karl-Edmund Prier SJ, biasa dipanggil Romo Prier, serta satu orang petugas kepolisian yang berusaha menenangkan pelaku, mengalami luka sabetan pedang dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sampai saat ini pihak kepolisian sedang menyelidiki motif tindakan teror tersebut.
Sehari sebelumnya, di tempat ibadah yang berbeda, tepatnya di Masjid Raya Aceh juga terjadi keributan, meski tidak ada korban jiwa. Ada pemuda yang mengganggu imam jamaah salat Ashar. Pemuda itu kemudian diamankan oleh pihak keamanan yang saat itu berjaga.
Sebelumnya, di lokasi dan hari yang berbeda, seorang tokoh agama Islam mengalami kekerasan serupa. Saat berada di rumahnya, di kawasan Kelurahan Cigondewah Kidul, Bandung Kulon, Kota Bandung, pintu rumah Ustaz Pranowo digedor dengan menggunakan linggis.
Ustaz Pranowo sempat keluar dan berbicara dengannya. Alih-alih mendengarkan, saat dinasihati, si pelaku itu justru bertambah marah dengan mengejar korban sambil membawa potongan pipa besi. Korban dikejar hingga 500 meter dan terjatuh di depan warung milik Eni.
Pelaku kemudian menganiaya korban di bagian kepala dan tangan hingga tak berdaya pada Kamis (1/2). (Jawapos.com, 5 Februari 2018).
Dari ketiga kasus tersebut, ada tiga pola yang serupa: objek kekerasan ini adalah tokoh agama, dilakukan di tempat ibadah, dan pelakunya disimpulkan mengalami gangguan kejiwaan (gila). Melihat peristiwa kekerasan tersebut, naif apabila kita melihat peristiwa itu sebagai kebetulan dan momentum yang terpisah.
Harus diakui, menganalisis tiga peristiwa tersebut dengan melihat figur individu dan konteks lokal memang sangat penting untuk mencermati pelbagai pertautan yang menjadi faktor pendorong mengapa pelaku melakukan tindakan tersebut. Namun, menilik pola keterulangan, keterhubungan, dan konteks, untuk melihat keterkaitan sebelumnya dalam kekerasan di Indonesia, mulai dari konflik Ambon, Poso, dan sebelumnya rentetan pembunuhan dukun santet pasca rezim Orde Baru, juga menjadi bahan perbandingan yang harus dilihat.
Di sini, pola kekerasan, pertarungan elite politik, dan kontra intelijen memainkan peranan penting bagaimana ruang publik ini dibentuk. Kondisi ini bukan hanya bentuk perang urat syaraf, melainkan alarm bagi rezim yang berkuasa sekarang.
Ada tiga amunisi yang sebelumnya dimainkan dalam upaya menggerogoti pemerintahan Joko Widodo oleh lawan-lawan politiknya, mulai dari anak PKI, antek aseng-asing, dan anti-Islam. Dari ketiga amunisi tersebut, sejauh ini belum ada yang berhasil. Karena itu, melihat tindakan kekerasan yang dialamatkan kepada tokoh agama menjadi dalih lain sebagai amunisi yang perlu diperhatikan di tengah menguatnya rumor kebangkitan PKI yang terus dihembuskan.
Di sini, melihat sejumlah kasus tersebut, tindakan kekerasan sering kali bukan untuk menunjukkan otoritas keagamaan terkait dengan siapa yang paling benar, apalagi sebagai bentuk amuk karena ketidaksukaan sensitivitas simbol keagamaan. Meskipun itu, setidaknya pasca Pilkada DKI, memberikan dampak signifikan di beberapa daerah. Selain memiliki motif ekonomi, kekerasan menciptakan efek ketakutan sebagai pesan penting di tengah konteks sosial politik.
Lebih jauh, tindakan kekerasan itu diharapkan menciptakan efek permusuhan dalam level akar rumput. Untuk konteks ini, Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Presiden 2019, upaya menciptakan bahwa pemimpin sekarang gagal menciptakan keamanan dan perdamaian menjadi penting dilihat. Di tengah situasi itu, orang kuat mesti hadir untuk menertibkannya.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur, regulasi pajak, penguatan kapitalisme negara di era Jokowi juga perlu dipahami bahwa itu semua bisa mengganggu oligarki yang tumbuh secara pesat di bawah kepemimpinan rezim Orde Baru dan beradaptasi dengan baik pasca rezim Orde Baru (Lihat Winters, 2011).
Sejumlah kebijakan yang dibuat Ahok, misalnya, sering mengebiri oligarki semacam ini yang berdampak terhadap distribusi ekonomi predator politik di bawahnya bisa dijadikan contoh. Walaupun, karena proses mobokrasi dengan menggunakan sentimen agama, Ahok akhirnya bisa dikalahkan (Widojoko, 2017).
Kecenderungan Jokowi di awal era pemerintahannya yang tidak percaya bahwa elite itu ada tidak hanya berbahaya, tapi justru bisa menjerumuskannya. Mesk demikian, dalam proses kepemimpinannya selama hampir empat tahun ini, ia tampak memiliki inisiatif politik di tengah kekuatan-kekuatan oligarki ini. Posisi sebagai masyarakat sipil, tidak memiliki partai, dan pedagang mebel disertai kecepatan belajar di tengah intervensi politik orang sekitarnya ternyata membuatnya mampu untuk melewati sejumlah tantangan tersebut.
Di tengah permainan tersebut, tantangan selanjutnya bagaimana sikap Jokowi menangani sejumlah kekerasan tersebut? Sikap dan aparatus keamanan di bawahnya menjadi penting untuk segera menyelesaikannya dengan melihat lebih jauh motif dari para pelaku tersebut.
Dalam konteks lebih jauh, pengalaman Jokowi berkunjung ke Afghanistan dan sejumlah negara yang dilanda konflik seharusnya menjadi refleksi kuat pemerintahannya untuk segera bertindak atas tindakan intoleransi dan kekerasan atas nama agama. Dalam melakukan hal tersebut, ia juga tidak akan ditinggalkan. Ada banyak individu dan organisasi sipil, baik sosial dan keagamaan, yang siap pasang badan untuk menjaga wajah keindonesiaan dan keragaman ini.
Wahyudi Akmaliah adalah peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.
Sumber : Dalih Orang Gila, Kekerasan dan Politik Oligarki Hanyalah Upaya untuk Menggulingkan Jokowi
Results 1 to 1 of 1
-
20-02-18, 23:53 #1
 Dalih Orang Gila, Kekerasan dan Politik Oligarki Hanyalah Upaya untuk Menggulingkan Jokowi
Dalih Orang Gila, Kekerasan dan Politik Oligarki Hanyalah Upaya untuk Menggulingkan Jokowi







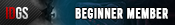




Share This Thread