Pemimpin Indonesia Joko Widodo tengah bergulat dengan kemerosotan komoditas global, di tengah kenaikan harga di dalam negeri. Terlepas dari upaya terbaik pemerintahnya, namun ekonominya hanya berhasil mencapai 5,07 persen pertumbuhan tahun lalu, di tengah konsumsi domestik yang lemah dan kemerosotan komoditas global. Meskipun Widodo adalah favorit untuk memenangkan pemilihan presiden saat ini, tapi masih harus dilihat apakah inisiatif ekonominya dapat memberinya jabatan presiden untuk kedua kalinya.
Oleh: Linda Yulisman (The Straits Times)
Ketika Presiden Joko Widodo berkuasa pada Oktober 2014, ia berjanji untuk mencapai 7 persen pertumbuhan ekonomi tahunan untuk Indonesia, di belakang dorongan infrastruktur yang ambisius.
Tetapi di tahun pertamanya menjabat, dia harus menerima kenyataan pahit, karena negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut, berkembang hanya 4,8 persen—laju paling lambat dalam enam tahun.
Dan terlepas dari upaya terbaik pemerintahnya, namun ekonominya hanya berhasil mencapai 5,07 persen pertumbuhan tahun lalu, di tengah konsumsi domestik yang lemah dan kemerosotan komoditas global yang telah memukul Indonesia, yang merupakan negara pengekspor utama minyak sawit dan batu bara.
Selasa (5/6) lalu, pemerintah Jokowi mengatakan bahwa pihaknya memangkas proyeksi pertumbuhan untuk tahun depan menjadi 5,2 hingga 5,6 persen, dari 5,4 hingga 5,8 persen, The Jakarta Post melaporkan. Ia juga memperkirakan hanya 5,18 persen pertumbuhan untuk tahun ini—turun dari 5,4 persen yang diuraikan sebelumnya.
Walau survei menunjukkan Jokowi sebagai favorit perusahaan untuk saat ini untuk memenangkan pemilihan presiden tahun depan, namun kegagalannya untuk memenuhi janji pertumbuhan ekonomi mungkin akan kembali menyerangnya.
Menurut sebuah survei oleh Poltracking Indonesia pada bulan Februari, antara 45 hingga 57 persen responden akan memilih Jokowi sebagai presiden, dibandingkan dengan saingan terdekatnya Prabowo Subianto, yang disurvei mencapai 20 hingga 33 persen.
Para pebisnis, investor, dan rakyat biasa, seperti mantan penjual elektronik, Gunawan, semuanya merasakan tekanan pertumbuhan Indonesia yang melambat dan lonjakan harga barang-barang kebutuhan pokok, terutama makanan pokok.
Gunawan—yang hanya memiliki satu nama—mengatakan bahwa ia sebelumnya bekerja di Glodok, Jakarta, di mana kuartal perdagangan tersibuk di negara itu dulu berada. Tapi kemerosotan penjualan sebagai akibat dari ekonomi yang lesu dalam dua hingga tiga tahun terakhir, membuat dia menutup toko tahun lalu.
“Naiknya harga bahan bakar, diikuti oleh lonjakan harga makanan pokok, telah membuat orang menunda membeli barang-barang lain,” kata pria berusia 44 tahun itu.
Dia mengatakan kepada The Straits Times bahwa dia mungkin tidak perlu memberikan suara lagi, karena politik sepertinya tidak dapat memperbaiki kehidupan rakyat biasa seperti dia.
Presiden Jokowi telah memotong pekerjaannya jika ia berharap untuk mengubah perekonomian Indonesia yang kurang berprestasi, bahkan saat ia bersiap untuk memulai kampanye pemilihan kembali pada bulan Agustus.
Yang pasti, dorongan infrastruktur pemerintahnya—seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan—telah berjalan dengan baik, kecuali untuk proyek-proyek seperti revitalisasi perkeretaapian Jakarta-Surabaya yang memiliki masalah pendanaan yang belum terselesaikan.
Tetapi konsumsi rumah tangga telah tumbuh lambat di Indonesia, meskipun itu menyumbang lebih dari 50 persen PDB.
Bank Dunia telah merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonominya untuk Indonesia, dari 5,3 persen dari-tahun-ke-tahun menjadi 5,2 persen, di tengah kondisi pengetatan moneter, potensi perang perdagangan global, volatilitas keuangan, dan kekhawatiran geo-politik.
“Faktor eksternal seperti itu memberikan tekanan pada kinerja ekspor Indonesia, maka dari itu juga pada pertumbuhan ekonomi domestik,” ujarnya menambahkan.
Aksi jual mata uang besar-besaran dalam beberapa bulan terakhir—terutama dipicu oleh moneter Amerika Serikat (AS) yang telah menarik dana asing ke negara ekonomi besar dunia—telah membuat rupiah Indonesia menjadi salah satu pemain terburuk di Asia.
Bulan lalu, rupiah jatuh di bawah 14.000 per dolar AS—terlemah sejak krisis keuangan Asia 1998 ketika rupiah jatuh ke rekor terendah 16.650 pada Juni tahun itu.
Untuk memastikan stabilitas, bank sentral dua minggu lalu menaikkan suku bunga acuannya, yang berfungsi sebagai pedoman bagi industri perbankan untuk menetapkan tingkat pinjaman, untuk kedua kalinya dalam beberapa minggu.
Ahli Ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan bahwa ini memiliki “dampak negatif pada ekonomi dengan cara pertumbuhan yang lemah”, dan menambahkan bahwa pemerintah telah memilih stabilitas di atas pertumbuhan.
Tapi ini mungkin akan dihargai oleh para pengusaha di Indonesia yang mengandalkan dollar dalam transaksi, dan meminjam uang dalam mata uang AS sebagai modal kerja.
Ini juga membuat Jokowi akan terlihat menepati janji kampanyenya untuk menjadikan Indonesia lebih ramah bisnis.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Mohammad Faisal, mengamati bahwa Jokowi telah memulai lebih banyak “kebijakan ekonomi populis” akhir-akhir ini.
Ini termasuk meningkatkan bantuan sosial untuk keluarga miskin, memberikan tunjangan Idul Fitri (Hari Raya Puasa) untuk Pegawai Negeri Sipil, personel militer, dan polisi, dan menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau meskipun harga minyak mentah naik.
“Langkah-langkah seperti itu akan menjadi faktor yang mempengaruhi popularitas Jokowi,” tambah Faisal.
Pusat Peneliti Strategis dan Internasional Arya Fernandes, menekankan bahwa Jokowi—seperti pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono—berharap untuk menarik pemilih dengan kebijakan ekonomi populisnya.
Walau Jokowi adalah favorit untuk memenangkan pemilihan presiden untuk saat ini, namun masih harus dilihat apakah inisiatif ekonominya dapat memenangkannya untuk jangka lima tahun kedua—sehingga dia dapat memenuhi janjinya untuk memberikan pertumbuhan 7 persen untuk Indonesia.
Sumber: Jokowi Gagal Capai Target PDB, Pemberian Kesempatan Kedua Harus Dipikirkan Lagi
Results 1 to 1 of 1
-
12-06-18, 22:11 #1

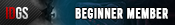


- Join Date
- Nov 2017
- Posts
- 167
- Points
- 165.40
Thanks: 0 / 1 / 1 Jokowi Gagal Capai Target PDB, Pemberian Kesempatan Kedua Harus Dipikirkan Lagi
Jokowi Gagal Capai Target PDB, Pemberian Kesempatan Kedua Harus Dipikirkan Lagi










Share This Thread