Tantangan bagi China terkait urusan Taiwan adalah bahwa munculnya identitas Taiwan adalah ancaman, tidak hanya soal klaim China di pulau itu, tetapi bahwa Taiwan berbicara bahasa non-CPC. Selain itu, Taiwan pun tengah mengembangkan modelnya pemerintahan berdasarkan nilai-nilai yang tidak hanya inklusif, tetapi juga membangun rasa universal.
Oleh: Chris Taylor (Asia Times)
Kisah Taiwan dan China telah lama didefinisikan oleh klaim kedaulatan oleh Tiongkok di pulau itu. Kisah “provinsi pemberontak” ini adalah warisan perang sipil China tahun 1927 hingga 1950 yang diperebutkan oleh Kuomintang (KMT) dan Partai Komunis China (CPC), dan yang mendorong KMT ke Taiwan.
Tapi hari ini perang itu jauh lebih besar daripada klaim kedaulatan pemerintah CPC di pulau itu. Kenyataannya, masalah kedaulatan mungkin jauh lebih sedikit hubungannya dengan perseteruan China di Taiwan daripada yang disadari oleh sebagian besar dari kita.
Ketika para jurnalis menulis tentang Taiwan, mereka umumnya membangkitkan demokrasi yang hidup dengan susah payah, yang jelas merupakan subjek yang oleh para otokrat Beijing lebih suka tak membicarakannya.
Tetapi produk sampingan dari evolusi demokrasi Taiwan juga menjadi kutukan bagi Beijing karena mereka menimbulkan ejekan terhadap klaim CPC yang banyak disebut telah mengevolusikan model tata pemerintahan “kuasai-semua-hal” yang berdasarkan—tak lain—Marxisme.
Ketika presiden China Xi Jinping terus mendorong model China yang berbasis Marxis, Taiwan tetap berada di jalur dengan eksperimen dalam keragaman yang tidak memiliki tempat di CPC China. Contoh yang jelas termasuk putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017 bahwa definisi undang-undang perkawinan saat ini sebagai hanya antara seorang pria dan wanita adalah tidak konstitusional, menetapkan kerangka waktu dua tahun untuk legalisasi pernikahan sesama jenis.
China baru melegalkan homoseksualitas pada tahun 1997, dan Departemen Kesehatan China baru menghapusnya sebagai penyakit “gangguan mental” pada tahun 2001. Sementara itu, sebuah laporan Universitas Peking 2016 menemukan bahwa hanya 15 persen responden gay China telah “jujur” kepada keluarga mereka, dan lebih dari setengah mengatakan mereka menderita diskriminasi sebagai hasilnya.
Wilayah lain divergensi antara Taiwan dan China adalah kebebasan pers. Indeks Kebebasan Pers Dunia terbaru, yang menempati peringkat 180 negara menurut “evaluasi pluralisme, independensi media, kualitas kerangka kerja legislatif dan keselamatan jurnalis” oleh LSM yang berbasis di Paris, Reporters Without Borders (RSF), menempatkan Taiwan di posisi ke-42 dari 180 negara. Ini menjadikannya negara dengan peringkat tertinggi di Asia Timur. China ditempatkan di posisi 176, menempatkannya dekat dengan bagian paling bawah daftar tersebut, di depan Suriah, Turkmenistan, Eritrea dan Korea Utara.
Tetapi mungkin yang paling memberi kejelasan kisah dua entitas politik ini adalah sikap terhadap kebijakan bahasa. Ambil contoh angkutan cepat massal di Taipei, dan Anda akan mendengar pengumuman dalam bahasa Inggris, Mandarin, Minnan (dialek dari Provinsi Fujian yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Hokkien dan secara lokal sebagai Taiwan) dan Hakka, bahasa kelompok etnis China yang paling banyak diaspora dan diucapkan oleh sekitar tujuh persen dari Taiwan. Hakka ditetapkan sebagai bahasa nasional oleh legislator pada bulan Desember tahun lalu.
Ke-42 dialek dari 16 bahasa resmi resmi Taiwan diakui pada bulan Juni tahun yang sama, mengharuskan pemerintah mengizinkan mereka digunakan untuk urusan legislatif dan hukum, dan bahwa pemerintah menetapkan landasan untuk mendukung bahasa dengan pengembangan sistem penulisan dan kamus.
Ini meninggalkan pertanyaan yang menjengkelkan tentang bahasa Taiwan, yang diyakini diucapkan oleh lebih dari 80 persen populasi. Di bawah aturan KMT, bahasa itu secara efektif dilarang dan siswa dihukum karena menggunakannya di sekolah.
Saat ini penggunaannya adalah wajib untuk pengumuman publik transportasi umum, tetapi rancangan undang-undang yang mempromosikan bahasa nasional, yang akan mengharuskan bahwa bahasa Taiwan termasuk dalam kurikulum sekolah, diharapkan akan segera disahkan.
Ini akan menempatkan bahasa Taiwan pada kedudukan yang sama dengan bahasa Mandarin sebagai bahasa nasional. Alasan mengapa langkah ini begitu lama dalam pembuatannya adalah ketakutan bahwa menjadikan Taiwan bagian dari kurikulum pendidikan 12 tahun wajib Taiwan akan dipandang oleh Beijing sebagai langkah lain dalam arah memformalkan independensi fungsional Taiwan.
Ini benar-benar provokatif karena kebijakan bahasa nasional China difokuskan pada bahasa Mandarin—dan sejauh bahwa banyak dari 298 bahasa yang diperkirakan di negara tersebut dianggap berada di bawah ancaman. Dalam laporan tentang Proyek Phonemica oleh The Atlantic pada tahun 2013, co-founder Phnonemica, Kelly Parker berkata: “Di banyak… tempat, generasi setelah anak-anak hari ini tidak dapat berbicara bahasa lokal.”
“Bahasa-bahasa ini juga tidak sedikit digunakan; kami melihat bahasa yang memiliki puluhan juta pembicara… Semakin banyak orang yang secara sadar menggunakan Bahasa Mandarin di rumah,” tambahnya.
Ini khususnya terjadi di daerah-daerah di China yang dianggap oleh Beijing sebagai masalah, seperti Tibet dan Xinjiang, di mana pemerintah tampaknya harus menghapus bahasa-bahasa non-Sinitik dari Tibet dan Uyghur.
Singkatnya, tantangan bagi China dalam berurusan dengan Taiwan adalah bahwa munculnya identitas Taiwan adalah ancaman tidak hanya untuk klaim China di pulau itu, tetapi bahwa Taiwan berbicara bahasa non-CPC yang didukung, dan protes yang terjadi, seperti gerakan Sunflower, terhadap politisi China dan Taiwan yang disesuaikan dengan China, sering dilakukan dalam bahasa Taiwan, bukan Mandarin.
Ancamannya juga adalah bahwa Taiwan sedang mengembangkan modelnya sendiri untuk pemerintahan berdasarkan nilai-nilai yang tidak hanya inklusif tetapi juga membangun rasa “universal”—tidak seperti akrobat intelektual yang membutakan pikiran yang diperlukan untuk memahami interpretasi Xi tentang Marxisme sebagai cahaya penuntun untuk pemerintahan global.
Ini mungkin hanya disimpulkan sebagai kebuntuan mengenai apakah perbedaan pendapat didefinisikan sebagai bertentangan dengan kepentingan negara atau apakah ia memiliki peran untuk dimainkan dalam memajukan kreativitas nasional yang inklusif.
Ini bukan perdebatan yang ditolerir China, tetapi Taiwan terus maju dengan itu semua—hanya karena pulau itu telah memungkinkan warganya untuk menjadi bagian dari argumen tentang bagaimana mereka mendefinisikan diri mereka dan bagaimana mereka memiliki masa depan mereka—dengan asumsi bahwa China memutuskannya secara militer tidak siap untuk menghentikan mereka melakukannya.
Sumber: Taiwan dan China: Pertempuran untuk Kedaulatan atau Keragaman?
Results 1 to 1 of 1
-
15-06-18, 18:26 #1

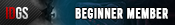


- Join Date
- Nov 2017
- Posts
- 167
- Points
- 165.40
Thanks: 0 / 1 / 1 Taiwan dan China: Pertempuran untuk Kedaulatan atau Keragaman?
Taiwan dan China: Pertempuran untuk Kedaulatan atau Keragaman?










Share This Thread