Minggu, 3 Agustus 2008
Hari ini, Mico mengajakku untuk berjalan-jalan ke salah satu mall di Jakarta.
Refreshing, katanya. Dia tidak ingin aku selalu berdiam diri terus-menerus di kamar.
“Mico, mau makan tahu gejrot hari ini!” sahutku tiba-tiba.
“Ga boleh makan cabe banyak-banyak. Kamu kalau makan itu pasti cabenya ga kira-kira. Udah badan kecil banget gitu, makannya cabe doang bukan makan yang lebih bisa bikin gede!” canda Mico.
“AAAA Micooo! Mau! Mau! Mau! Pokoknya mau!”
“Ngidam, Rei?”
“Iya kali! Pokoknya mau! Mau siomay, mau ketoprak, mau gorengan!”
“Hah? Beneran ngidam kayaknya kamu Rei. Yaudah kira-kira biasanya ada di mana? Aku jarang makan yang kayak begitu.”
“Biasanya di dekat perempatan di depan sana ada.” sahutku sambil menunjuk ke depan.
“Yaudah. Yang di depan supermarket itu kan? Nanti aku sekalian mau beli barang dulu, dititipin sama mama aku kemaren, oke?”
Setibanya di depan supermarket, hanya ada satu gerobak yang berjualan. Maklum, baru pukul 4. Para penjaja makanan baru akan berjualan mulai jam 5 sore.
“Tahu gejrotnya belom ada. Tapi itu ada siomay. Oke, aku makan siomay aja. Uda kangen makan pare!”
Sejak SMA 1, aku sangat menyukai pare, entah itu direbus, atau dimasak dengan bumbu apapun. Terkadang Ibu pun suka memasakkan pare hanya untuk diriku, karena tidak ada yang menyukai pare di keluargaku.
“Kamu mah pare mulu. Ga ada enak-enaknya itu makanan. Pahit, kayak minum obat. Pantes tuh muka kamu pahit banget keliatannya!”
“Yeeee, biarin aja. Suka-suka aku dong! Emang masalah buat kamu?”
“Masalah ga ya? Maunya masalah atau engga? Hahaha”
“Bawel ah, aku turun duluan yaaa.”
“Hati-hati, Rei sayang. Aku ke supermarket dulu juga.”
Akhirnya aku menghampiri gerobak siomay itu, berharap akan mendapatkan pare yang sudah idam-idamkan.
“Mas, dibungkus ya.” kataku kepada
mas-mas yang berjualan.
“Mau berapa?”
“Ini kok ditanya mau berapa ya. Bukannya biasa kalau beli siomay itu, kita milih dulu mau apa aja terus baru dia itungin harganya berapa? Apa ini beli siomay sekarang uda paketan ya?” sahutku dalam hati.
“Hah? Mau berapa gimana ya?” tanyaku balik.
“Iya mau 1 atau berapa,
dek?”
“Jadi beli siomay itu sekarang bisa beli 1 biji doang gitu? Apaan dah ini. Kok makin aneh beli siomay aja pake berapa.” pikirku dalam hati, kebingungan.
“Kalau gitu saya liat dulu aja bang ada apa aja.”
“Mau lihat apanya,
dek?”
“Iya saya lihat-lihat dulu ada apa. Ada pare ga,
mas?” tanyaku, karena tidak semua penjual siomay menjual pare.
“HAH? Pare? Pare apa?”
“Pare ya pare,
mas.” ujarku gusar.
“Hah? OOOHH!
Adek maunya siomay ya?”
“Lah? Ya iya,
mas”
“OOOHHH! Kamu carinya siomay? Ga ada yang jual siomay di sini.” kata mas-mas yang berjualan itu sambil tersenyum menahan tawa.
Salah tingkah. Dalam keadaan panik, aku masih mengumpulkan sisa kesadaranku untuk melihat kata-kata yang tertulis di kaca gerobak itu. “S T O A Y A M”. Oh, jadi ini soto. Hanya saja stiker huruf O di gerobak itu sudah terlepas. Lalu di bagian mananya sampai aku bisa membaca itu “SIOMAY”? Ternyata salah tingkah rasanya seperti ini. Apa yang harus dilakukan saat ini? Mico sepertinya masih sangat lama di dalam supermarket itu dan kunci mobil pun ada di dirinya. Ah, sudahlah.
“Errr, yaudah deh,
mas. Sotonya satu aja.”
“Sotonya 1 aja,
dek?” masih sambil tersenyum menahan tawa.
“Hmm, i-iya.”
Sore ini, semua makanan yang tadinya terbayang olehku begitu nikmat, menjadi sangat tidak nikmat. Mico keluar dari supermarket dan memanggilku untuk naik ke mobil. Saat di mobil, Mico pun membuka sesi tanya-jawab,
“Kok ga dimakan siomay-nya? tanyanya kebingungan sambil melihat ke arah kantong plastik hitam yang aku pegang.
“Ga ada siomay-nya.”
“LOH? Terus itu apa? Tadi katanya ada yang jual siomay.”
“Ga jadi, beli soto jadinya.”
“Loh? Soto darimana? Katanya tadi cuma ada siomay?”
“Jangan tanya-tanya ah. Nanti aja kalau mau cerita soal itu. Ah, Mico, mampir ke rumah aku dulu lagi aja ya bentar. Nurunin sotonya dulu. Mumpung masih deket dari rumah aku juga kan.”
“Hmm, okelah sayang.”
Raut muka Mico memang berubah, ah tapi mau diapakan lagi. Ini juga bukan salahku sepenuhnya. Lalu, salah siapa? Ah, aku juga tidak tahu. Namun. Memang moodku sudah berubah sore itu. Entah, sebenarnya kejadian yang tadi ku alami itu memang termasuk kejadian yang lucu, tapi aku memang enggan untuk menertawakan kebodohanku saat ini.
Akhirnya sisa hari ini aku habiskan dengan bersenang-senang dengan Mico. Ia mengajarkan aku bagaimana bermain
ice-skating berjam-jam, namun mungkin memang bukan bakatku di bidang itu. Aku sempat terjatuh beberapa kali dan aku harap tidak akan ada memar kebiruan keesokan harinya.
Aku dan Mico sudah hampir 1 bulan menjalani hubungan ini, dan aku perasaan sayang itu semakin lama semakin bertumbuh. Tiba-tiba aku merasa bahwa aku harus membelikan sesuatu untuk Mico dan memberikannya saat perayaan 1 bulanan kita. Namun, apa yang harus dibeli?
Sambil memikirkan apa yang harus dibeli, aku masih mengingat-ingat apa saja yang dilakukan hari ini. Suatu kemajuan hari ini aku dapat menghabiskan setengah hari di luar bersama orang lain. Hari ini perlu diberi sebuah judul, “SM : Siomay atau Soto bersama Mico”. Aku merasa sangat baik hari ini dan aku akhirnya menutup mataku malam ini dengan sebuah senyuman.
Selasa, 5 Agustus 2008
Setelah bel pulang berbunyi, aku segera berlari ke arah tempat parkir mencari mobilku, ups, mencari supirku yang berada di dalam mobil lebih tepatnya. Aku tidak ingin orang mengira aku dapat menyetir mobil. Ayah tidak akan membiarkan aku menyetir sendiri. Lagipula, untuk apa sebuah mobil, jika aku hanya tahu jalan menuju sekolah dan sekitar rumahku. Tapi, untuk hari ini, aku bertanya,
“Pak, bapak tahu toko buku yang lengkap di mana?” tanyaku pada supir.
“Yang lengkap ya? Ada sih, Cuma agak jauh, gapapa?”
“Gapapa, pak. Soalnya ini penting.”
“Pulang dulu atau langsung pergi?”
“Langsung aja, pak. Aku yang telponin Ibu aja.”
Aku memang selalu harus memberitahu ada di manakah diriku jika ingin berpergian. Ibu akan sangat marah jika tahu bahwa aku ada di suatu tempat dan tidak memberitahukannya.
Setibanya di toko buku itu, aku segera menghampiri tempat yang menjual bahan-bahan untuk
scrapbook3. Aku sudah membulatkan niatku untuk membuat satu
scrapbook untuk Mico. Sebenarnya, aku tidak yakin ia akan menyukai pemberianku; dan terlebih aku memang tidak terlalu berbakat dalam hal semacam men-
desain. Tentunya, aku tidak ingin meminta bantuan Sunny, karena ini adalah hadiah khusus yang aku ingin buat dengan tanganku sendiri untuk Mico. Rencanaku adalah membuat kira-kira beberapa kenangan menjadi satu, dan aku akan memasukkan satu atau dua puisi ciptaanku untuknya. Bahan-bahan itu akhirnya ku bawa pulang ke rumah. Aku rela menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli bahan-bahan ini, asalkan untuk Mico seorang.
Rabu, 6 Agustus 2008
Hari yang ku tunggu-tunggu telah tiba! Aku sudah membuat janji dengan Mico setelah pulang sekolah dan pada akhirnya bel itu berdering. Aku segera mengambil ponselku dan menelepon Mico. Hari ini aku telah berbohong pada Ibu. Aku mengatakan bahwa hari ini aku tidak perlu dijemput, karena aku harus mengerjakan tugas kelompok. Ibu memang tidak pernah curiga bahwa aku tiba-tiba peduli dengan tugas, karena ia memang selalu berharap aku dapat kembali seperti dahulu, saat meraih juara kelas.
Ponsel Mico tidak diangkat. Aku sudah berusaha mencoba meneleponnya hingga enam kali, dan hasilnya nihil. Aku tinggalkan pesan singkat berisikan,
“Aku masih nungguin kamu loh, Mico. Aku hari ini udah minta ga dijemput supaya bisa langsung ketemu kamu. Kamu di mana?”
“Apa Mico benar-benar lupa hari ini adalah hari 1 bulan kita bersama? Apa Mico melupakan janji temu kita hari ini? Apa aku harus menyusul Mico ke sekolahnya? Mico, mengapa di hari paling penting kita, kamu melupakan aku seperti ini?”
Berbagai pikiran-pikiran negatif silih-berganti muncul di dalam pikiranku. Mico tidak pernah mengabaikan telepon ataupun pesan singkat dariku. Namun, mengapa harus hari ini? Dua jam telah berlalu, waktu telah menunjukkan pukul 3 sore. Tak ada tanda-tanda kemunculan Mico di depan gerbang sekolahku. Keadaan sekolahku pun sudah mulai sepi, aku hanya melihat ada beberapa anak-anak yang ikut ekstrakulikuler futsal di lapangan. Ini kali pertama aku masih berada di sekolah hingga sesore ini.
“Drrrtt.. Drrrttt...”
Ah, ponselku akhirnya bergetar. Dengan harap-harap cemas, aku membuka ponselku dan menemukan,
“Kamu pulang jam berapa?”
Ah, Ibu. Bagaimana aku harus menjawab Ibu, sedangkan aku masih belum menemui Mico. Dengan cemas, aku membalasnya,
“Secepatnya, Bu. Nanti aku dianter sama temenku kok pulangnya.”
Diantar? Apa Mico benar-benar akan mengantar aku pulang? Apa Mico akan datang hari ini? Sudahlah, apapun yang terjadi nant, aku memang tidak ingin cepat sampai di rumah. Jika memang Mico tidak menemuiku hari ini, aku lebih memilih untuk menghabiskan waktuku di depan gerbang sekolah ini, sendiri.
“Dddrrrtt... Drrttt...”
Getaran ponselku lagi. Apakah ini Ibu ataukah Mico? Dengan cemas, aku kembali membuka ponselku sambil berharap itu adalah Mico.
“Sayang, maaf. Aku baru inget hari ini aku ada ekskul basket. Tadi hapenya aku taro di locker. Ini aku baru selesai latian, kamu masih nunggu di sekolah? Aku ke sana sekarang. Tapi mungkin akan macet, jadi kira-kira setengah jam lagi baru sampe. Masih mau ketemu aku atau besok aja? Aku kosong kok besok.”
Aku tidak tahu harus membalas apa, mengapa Mico dapat setega ini padaku? Bukankah selama ini dia yang paling mengerti aku? Mengapa kemarin saat aku membuat janji dengannya, ia tidak mengungkit sama sekali tentang ekstrakulikulernya itu? Mengapa harus saat ini setelah aku menunggu dua setengah jam lamanya. Namun, aku tetap tegar menahan air mataku, dan membalas pesan singkat itu,
“Iya, aku masih nunggu di depan gerbang sekolah. Hari ini aja kalau kamu ga cape. Kalau cape, yaudah ga usah ketemuan lagi aja. Besok aku mau di rumah soalnya.”
Kacau. Itulah perasaanku saat ini. Aku meremas plastik berwarna hitam di tangan kiriku, tempat dimana scrapbook untuk Mico berada. Tidak, aku tidak boleh menyerah sampai di sini. Aku ingin bahagia, dan kali ini, aku akan belajar untuk menerima kesalahannya.
Jam di ponselku menunjukkan pukul 4 sore dan Mico kini berada tepat di depanku, namun aku benar-benar tidak tahu apa yang harus ku ucapkan saat ini. Antusiasmeku untuk hari ini telah pudar.
“Rei? Rei? Kok bengong aja?”
“Hah? Oh. Maaf.”
“Kamu marah sama aku?”
“Hmmm, engga.”
“Terus? Kamu keliatan pucat Rei, kamu sakit?” tanya Mico sambil tersenyum.
Ah, senyuman itu. Ia memang selalu dapat menenangkan aku di saat aku teramat sedih sekalipun, tapi tidak untuk hari ini. Kepalaku sangat sakit dan pandanganku seakan memudar perlahan. Aku bahkan tidak bisa berkonsentrasi lagi untuk menjawab pertanyaan terakhir Mico.
“Rei? Rei? Kamu kenapa?”
Sesaat badanku melimbung, dan dengan cepat badan ini sudah di pelukannya. Mico segera menggendongku ke dalam mobil dan membawaku ke rumah sakit terdekat. Aku memang tak sadarkan diri sekitar satu jam, dan Mico tetap di sampingku hingga akhirnya aku terbangun.
“Mico, aku kenapa?”
“Ga ada hal serius kok. Nanti kalau kamu udah baikan, kamu aku anterin ke rumah.”
“Dokter bilang aku kenapa?”
“Ga apa-apa. Cuma dibilang tekanan darahmu menurun drastis, gara-gara kamu ga makan dan terlalu lelah hari ini.”
Mico berubah sangat dingin padaku. Apa ini karena dia terlalu khawatir dengan keadaanku? Tapi, ke mana panggilan sayang itu pergi? Ah, sudahlah. Sesaat pandanganku terpaku pada infus yang disuntikkan pada tangan kiriku. Aku baru saja menyadari bahwa lengan jaket ini telah digulung hingga mencapai lenganku, guna menyuntik infus ini. Sesaat aku membeku, melihat semua goresan itu tertera jelas di sana tanpa tertutupi.
Kepalaku seakan melimbung untuk kedua kalinya hari ini. Tapi, untunglah kini aku sedang berbaring di tempat tidur rumah sakit. Namun, pingsan di tempat ini bukanlah pilihan yang tepat. Aku harus segera pulang, sebelum Ibu dan Ayah mencariku. Sudah terlalu banyak masalah yang harus aku selesaikan hari ini, dan membuat orangtuaku panik bukanlah suatu pilihan.
“Mico, aku mau pulang. Aku udah ga kenapa-kenapa kok.”
“Bener?”
Aku mengangguk lemah. Mico tidak pernah sedingin ini padaku. Tak ada lagi kecupan di pipi untuk menenangkan diriku. Perubahan pesat Mico ini membuat aku seakan merasa semakin lemah dan tak berdaya. Aku membutuhkannya.
“Oke, aku panggilin dokter supaya kamu bisa diurus dan aku bisa cepet anterin kamu pulang.”
Sebelum ia beranjak dari kursi di sebelah tempat tidurku, aku berusaha sekuat tenaga untuk bertanya,
“Mico, kamu ga seneng kita hari ini satu bulanan? Aku ngajak kamu ketemu, buat ngerayain satu bulanan ini bareng.”
“Dan akhirnya apa, Rei? Aku akhirnya nemenin kamu di rumah sakit doang kan? Ditambah lagi, kenapa kamu ga pernah cerita?”
“Soal apa?”
Aku tahu, suatu hari nanti ia pasti akan mengetahui dan menanyakan tentang siapa aku sebenarnya, apa yang aku lakukan selama ini saat sendirian di kamar, dan terlebih yang paling aku takutkan adalah saat ia bertanya darimana asal semua goresan itu ada. Akan tetapi, aku mohon, tidak saat ini, tidak hari ini.
Ia hanya berdiam diri di sana untuk beberapa menit, melihat ke arah tangan kiriku, dan berjalan ke arah pintu. Ia sempat membalikkan badannya, menatapku, dan dengan tegas mengatakan,
“Maaf kalau aku memang lupa hari ini adalah hari penting kita, tapi ada hal yang lebih penting yang seharusnya kamu ceritakan padaku sebelumnya, daripada akhirnya aku tahu sendiri apa yang selama ini kamu lakukan pada dirimu. Aku kecewa.”
“Mi-Mico...”
Sebelum kalimatku selesai terucap, ia sudah keluar untuk memanggil dokter. Hujan lebat diiringi guntur yang menyambar tiba-tiba mengguyur bumi, seakan-akan ikut bersedih atas aku. Air mata ini jatuh tak terbendung lagi. Aku terisak sejadi-jadinya, aku membutuhkannya di saat-saat seperti ini. Tapi apa jadinya jika akulah penyebab ia pergi meninggalkan diriku? Akankah ia mendengarkanku, meski untuk yang terakhir kalinya?













 itu Sunny, bukan Rainie
itu Sunny, bukan Rainie 










 "Can you BE any more clueless?"
"Can you BE any more clueless?"


















 soalnya besok mau ke tempat sponsor lagi
soalnya besok mau ke tempat sponsor lagi  "
"
 Spoiler untuk Hai :
Spoiler untuk Hai :





















 "The only way to do great work is to love what you do" ♥
"The only way to do great work is to love what you do" ♥
 Spoiler untuk loli gagal :
Spoiler untuk loli gagal :



















 suer gw bingung bacanya @_@“Jangan tanya-tanya ah. Nanti aja kalau mau cerita soal itu. Ah, Mico, mampir ke rumah aku dulu lagi aja ya bentar. Nurunin sotonya dulu. Mumpung masih deket dari rumah aku juga kan.”
suer gw bingung bacanya @_@“Jangan tanya-tanya ah. Nanti aja kalau mau cerita soal itu. Ah, Mico, mampir ke rumah aku dulu lagi aja ya bentar. Nurunin sotonya dulu. Mumpung masih deket dari rumah aku juga kan.”

 .. mico gak bilang langsung, tapi akhirnya fetish Rainie mulai terungkap..
.. mico gak bilang langsung, tapi akhirnya fetish Rainie mulai terungkap.. 


























 "The only way to do great work is to love what you do" ♥
"The only way to do great work is to love what you do" ♥







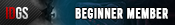

 Reply With Quote
Reply With Quote






Share This Thread