Prancis dan Inggris berkomitmen untuk menegakkan kebebasan navigasi di Laut China Selatan yang diperebutkan, dalam sebuah perlawanan sekutu terhadap militerisasi China di daerah itu. Keduanya juga memiliki kepentingan perdagangan yang signifikan di daerah tersebut, berkat hubungan perdagangan yang berkembang pesat dengan bekas negara jajahan di Asia.
Oleh: Richard Javad Heydarian (Asia Times)
Eropa masuk ke dalam kontes supremasi yang meningkat di Laut China Selatan.
Dalam apa yang bisa menjadi pergeseran yang merambat, Prancis dan Inggris telah menunjukkan komitmen mereka untuk mencegah satu negara, yaitu China, dari mendominasi jalur laut vital yang dilalui perjalanan perdagangan senilai lebih dari $5 triliun setiap tahun.
Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSC) dan negara nuklir status quo, kedua negara Eropa tersebut menambahkan beban geopolitik yang signifikan terhadap upaya berkelanjutan untuk membatasi ketegasan maritim China di kawasan tersebut.
Kedua negara Eropa tersebut diperkirakan akan melakukan patroli rutin di wilayah itu untuk menegakkan kebebasan navigasi dan penerbangan. Prancis dan Inggris juga memiliki kepentingan perdagangan yang signifikan di daerah tersebut, berkat hubungan perdagangan yang berkembang pesat dengan bekas negara jajahan di Asia. Prancis juga masih memiliki beberapa negara Pasifik yang menampung sejumlah besar warganya.
Seiring Amerika Serikat (AS) berjuang untuk memeriksa ambisi angkatan laut China, negara-negara sekutu besar lainnya semakin meningkatkan peran. Selama empat tahun terakhir, Angkatan Laut AS telah melakukan apa yang disebut Kebebasan Operasi Navigasi (FONOPS) untuk menantang klaim teritorial dan perluasan jejak militer China di daerah tersebut.
Namun, patroli dan operasi angkatan laut tampaknya belum cukup kuat untuk menghalangi militerisasi cepat China atas fitur-fitur yang dikendalikannya. Memang, Beijing telah menunjuk pada FONOPS Amerika sebagai provokasi yang membenarkan langkahya baru-baru ini untuk membentengi posisinya di wilayah maritim tersebut.
Pada tahun 2015, Presiden China Xi Jinping dilaporkan berjanji kepada mitranya dari Amerika—Presiden saat itu Barack Obama—bahwa China tidak akan memiliterisasi fitur lahan yang disengketakan di Laut China Selatan.
Janji itu, bagaimanapun, telah benar-benar dilanggar, di mana China baru-baru ini menyebarkan pesawat pengebom berkekuatan nuklir, rudal permukaan-ke-udara, rudal balistik anti-kapal, dan peralatan pengganggu elektronik ke pulau-pulau yang diklaimnya.
Beijing telah berulang kali menggambarkan kegiatan militerisasi dan reklamasinya di wilayah tersebut sebagai tindakan “defensif” terhadap agresi yang dilakukan Amerika.
Selama Dialog Shangri-La yang baru-baru ini disepakati—sebuah pusat pembicaraan keamanan yang diadakan di Singapura—Letnan Jenderal He Lei, Wakil Presiden Akademi Militer Tentara Pembebasan Rakyat China, mengatakan: “Semua pulau adalah bagian dari wilayah China dan kami memiliki catatan sejarah yang diakui oleh hukum internasional… Senjata-senjata tersebut telah dikerahkan untuk pertahanan nasional.”
AS telah berulang kali mengkritik tindakan China, tetapi belum mengungkap strategi “FONOP Plus” yang baru dan lebih efektif. Ketika ditanya apakah Washington akan pergi menyelamatkan negara-negara pengklaim yang lebih kecil seperti Filipina—sekutu perjanjian—Menteri Pertahanan Amerika James Mattis menyatakan keberatan.
“Kami berdiri mendukung sekutu perjanjian kami, tetapi ini adalah diskusi antara pemerintahan saat ini di Manila dan di Washington. Ini bukan masalah yang dapat dijawab sesederhana seperti yang ditunjukkan pertanyaan Anda,” kata Mattis kepada para hadirin setelah pidatonya yang sangat diantisipasi di KTT keamanan tersebut.
Dengan Amerika yang gagal memberikan dukungan kategoris kepada sekutu perjanjiannya, banyak yang bertanya-tanya apakah negara pengklaim yang lebih kecil—yaitu Malaysia, Taiwan, Brunei, dan Vietnam—memiliki cukup insentif dan bahkan kemampuan untuk melawan militerisasi China yang tak kenal lelah di daerah tersebut.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte baru-baru ini mengumumkan tiga “garis merah” di daerah itu, jika China atau negara lain yang terlibat akan menjadi penyebab perang. Namun, kepala pertahanannya, Delfin Lorenzana, menyesalkan kurangnya kapabilitas angkatan lautnya untuk mencegah China membentuk zona pengecualian di daerah itu.
“Saat ini, kami tidak memiliki kemampuan bahkan untuk menunjukkan kepada pihak lain bahwa kami mampu. Kami tidak mampu. Kami tidak memiliki kapal modal. Kami tidak memiliki senjata,” kata Lorenzana pada bulan lalu ketika meminta Kongres Filipina untuk mengalokasikan dana untuk keamanan maritim. “Jika mereka menghalangi orang-orang kami untuk mengirim ulang kekuatan kami di sana di Spratly, lalu apa yang bisa kami lakukan?”
Apakah negara-negara Eropa Inggris dan Prancis akan membantu memberikan pencegahan yang lebih kuat belumlah jelas. Dalam pidatonya pada pertemuan puncak tersebut, Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly bertujuan untuk menarik garis di sekitar komitmen Prancis untuk keamanan Laut China Selatan.
“Prancis bukan bagian dari perselisihan teritorial di daerah itu, dan tidak akan, tetapi kami bersikeras pada dua prinsip aturan internasional berbasis aturan: Sengketa harus diselesaikan dengan cara dan negosiasi legal, bukan oleh keadaan yang harus diterima (fait accompli), dan kebebasan navigasi harus dijunjung tinggi,” kata Kepala Pertahanan Prancis.
“Kami percaya negosiasi adalah cara yang tepat. Sementara itu, kita harus jelas bahwa fait accompli tidak diterima,” tambahnya mengacu pada langkah-langkah terbaru China di daerah tersebut.
Menteri Pertahanan Prancis juga menegaskan bahwa walau negaranya menyambut Kode Etik di wilayah yang disengketakan, namun setiap perjanjian akhir, “harus mengikat secara hukum, komprehensif, efektif, dan konsisten dengan hukum internasional.”
China dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara telah secara tidak setuju bergulat dengan pengembangan satu kode yang disetujui bersama, yang secara hukum dapat dilaksanakan untuk Laut China Selatan selama hampir dua dekade.
Parly juga mengatakan bahwa, “Prancis bukan bagian dari sengketa teritorial (di Laut China Selatan) dan… Prancis sama sekali tidak berperang dengan China,” tetapi bahwa negaranya akan meningkatkan FONOPS-nya sendiri di wilayah yang diperebutkan tersebut. “Eropa telah mulai memobilisasi lebih luas untuk mendukung upaya ini… Saya percaya kami harus memperluas upaya ini lebih jauh,” tambahnya.
Dalam pidatonya, Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson, mengeluarkan hinaan tidak langsung pada China, dengan menyebut “negara-negara yang semakin agresif” yang “melanggar akses regional, kebebasan, dan keamanan melalui pemaksaan”, sebagai ancaman terhadap tatanan berbasis aturan di wilayah Indo-Pasifik.
“Kami percaya negara-negara harus mengikuti aturan yang disepakati, tetapi ini diabaikan oleh beberapa pihak, dan apa yang dilakukannya itu merusak perdamaian dan kemakmuran semua bangsa,” kata Williamson di KTT Shangri-La. “Kami harus menjelaskan bahwa negara-negara perlu bermain sesuai aturan dan ada konsekuensi untuk itu,” tambahnya.
Serupa dengan Prancis, Inggris juga telah melakukan FONOP di Laut China Selatan. Baru-baru ini Inggris mengerahkan dua kapal perang besar, HMS Albion dan HMS Sutherland, untuk menantang klaim luas China di daerah tersebut.
Setelah bertahun-tahun berlalu, sekutu Eropa Amerika mulai menanggung beban yang semakin besar untuk mencegah dominasi China atas perairan internasional tersebut. Tetapi dengan masuknya mereka, pertikaian maritim tersebut telah menjadi campuran yang lebih rumit dari negara-negara super yang berdesakan dan berkelahi.
Sumber: Eropa Pinjam Kekuatan Amerika di Laut China Selatan
Results 1 to 1 of 1
-
07-06-18, 06:35 #1

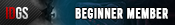


- Join Date
- Nov 2017
- Posts
- 167
- Points
- 165.40
Thanks: 0 / 1 / 1 Eropa Pinjam Kekuatan Amerika di Laut China Selatan
Eropa Pinjam Kekuatan Amerika di Laut China Selatan










Share This Thread